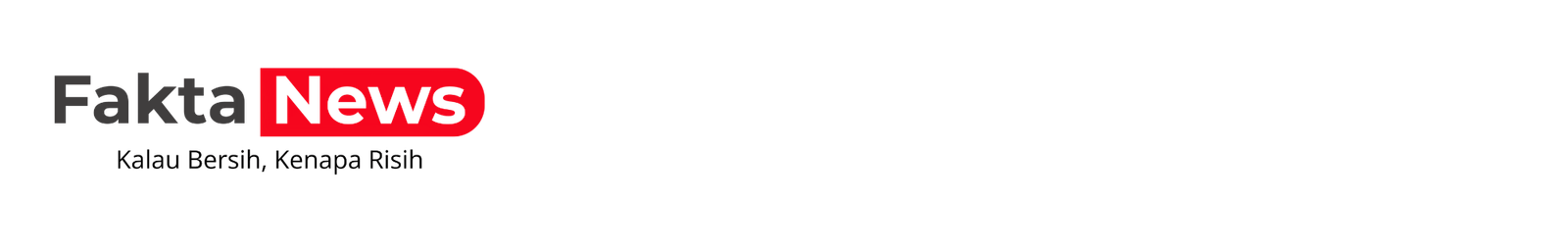Oleh : Jhojo Rumampuk
Fakta News – Opini. Banjir yang berulang di pusat Ibu Kota Kabupaten Pohuwato bukanlah musibah yang jatuh dari langit. Ia lahir dari kerusakan yang diciptakan manusia, dipelihara oleh pembiaran, dan kini dipoles dengan uang. Dalam pusaran itulah muncul satu fakta yang patut digugat bersama: aliran dana ratusan juta rupiah dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dibungkus dengan istilah “Biaya Gotong Royong”.
Berdasarkan data yang diperoleh, pada November 2025 terdapat dana sekitar 464 juta yang dihimpun dari 29 pengusaha PETI. Dana itu disebut-sebut diperuntukkan bagi kegiatan normalisasi sebagai langkah antisipasi banjir di Desa Teratai, Marisa Utara, dan Palopo. Tiga desa yang selama ini menanggung dampak langsung dari rusaknya lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal.
Dana tersebut tidak digunakan untuk normalisasi, perbaikan drainase atau pemulihan daerah aliran sungai, melainkan dialihkan untuk pembangunan empat unit rumah warga, satu unit di Desa Bulangita, dan tiga unit di Desa Teratai. Tidak ada penjelasan terbuka, tidak ada laporan resmi yang mudah diakses publik, dan tidak ada kejelasan mekanisme pengambilan keputusan.
Dari titik ini, pertanyaan paling mendasar harus diajukan: siapa yang sebenarnya menikmati dana PETI tersebut, dan siapa yang justru menanggung dampaknya?
Uang menjadi alat tawar. Kritik mereda. Penindakan tak kunjung datang. Pertama, dalam situasi seperti ini, dana gotong royong berfungsi sebagai tameng sosial dan bahkan politik agar aktivitas ilegal tetap berlangsung tanpa gangguan berarti.
Pihak yang berpotensi menikmati adalah aktor-aktor lokal yang memiliki kewenangan atau pengaruh dalam pengelolaan dana tersebut. Tanpa transparansi, publik tidak pernah tahu siapa yang mengoordinasikan pengumpulan dana, siapa yang memutuskan penggunaannya, dan mengapa alokasinya menyimpang dari tujuan awal. Dalam ruang gelap semacam ini, kepentingan personal dan politik lokal sangat mungkin bermain.
Pihak ketiga yang menikmati, secara langsung adalah penerima manfaat pembangunan rumah. Namun di sini harus ditegaskan penerima rumah bukanlah pihak yang patut disalahkan. Mereka berada di posisi paling lemah dalam rantai ini. Justru fakta bahwa bantuan diarahkan ke individu, bukan pemulihan sistemik, menunjukkan bagaimana dana PETI digunakan untuk memecah fokus persoalan.
Sementara itu, pihak yang menanggung dampak jauh lebih luas dan lebih dalam. Pertama adalah lingkungan hidup. Sungai yang dangkal, hulu yang rusak, dan daerah aliran sungai yang kehilangan fungsi ekologis tetap dibiarkan. Empat unit rumah tidak akan menghentikan banjir. Tidak akan mengembalikan tanah yang tergerus. Tidak akan menahan lumpur dan limbah yang terus mengalir dari wilayah PETI.
Kedua adalah masyarakat luas di Pohuwato, khususnya warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Mereka tetap menghadapi risiko yang sama, baik rumah terendam, akses terputus, mata pencaharian terganggu. Mereka tidak menikmati dana 464 juta itu, tetapi merekalah yang akan pertama kali terdampak ketika hujan turun dan sungai meluap.
Ketiga adalah desa-desa yang disebut sebagai sasaran awal program. Marisa Utara dan Palopo, misalnya, nyaris tak terdengar mendapatkan manfaat langsung dari dana yang disebut untuk mereka. Ini menimbulkan kesan bahwa nama desa hanya dijadikan legitimasi administratif, sementara realisasi di lapangan berjalan dengan logika lain.
Keempat,dan yang paling fatal adalah supremasi hukum. Ketika dana dari aktivitas ilegal diterima, dikelola, dan digunakan tanpa proses hukum, maka pesan yang sampai ke publik sangat jelas, PETI bukan masalah serius. Ia bisa dinegosiasikan. Bisa dikompensasi. Bisa “diselesaikan” dengan uang.
Di titik ini, Daerah kehilangan wibawanya. Fungsi pemerintah dalam mitigasi bencana dan pemulihan lingkungan digantikan oleh pelaku perusakan itu sendiri. Aparat penegak hukum tampak absen, atau memilih diam. Pembiaran ini perlahan membentuk normal baru: kejahatan lingkungan yang dilegalkan oleh keheningan.
Gotong royong, dalam makna sejatinya, adalah solidaritas warga untuk kepentingan bersama. Namun ketika istilah itu dilekatkan pada dana PETI, maknanya berubah total. Ia bukan lagi nilai sosial, melainkan topeng moral. Topeng untuk menutupi asal-usul uang. Topeng untuk meredam kegaduhan. Topeng untuk mempertahankan status quo.
Opini ini tidak bertujuan menuduh individu tertentu tanpa dasar. Namun publik berhak tahu dan bertanya. Uang 464 juta itu bukan angka kecil. Ia cukup besar untuk menjadi petunjuk bahwa PETI di Pohuwato bukan aktivitas sporadis, melainkan industri ilegal yang terorganisir dan memiliki daya tawar.
Jika praktik ini dibiarkan, maka banjir berikutnya hanya tinggal menunggu waktu. Dan ketika itu terjadi, masyarakat akan kembali mendengar narasi lama: cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, faktor alam. Padahal di balik itu semua, ada cerita tentang uang, pembiaran, dan gotong royong yang salah alamat.
Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang menikmati dan siapa yang terkena dampak” menemukan jawabannya sendiri. Yang menikmati adalah mereka yang merusak dan dibiarkan. Yang menanggung dampak adalah mereka yang tak pernah diajak bicara. Dan selama negara memilih diam, Pohuwato akan terus berada di antara emas ilegal dan banjir yang tak pernah benar-benar diatasi.
![]()