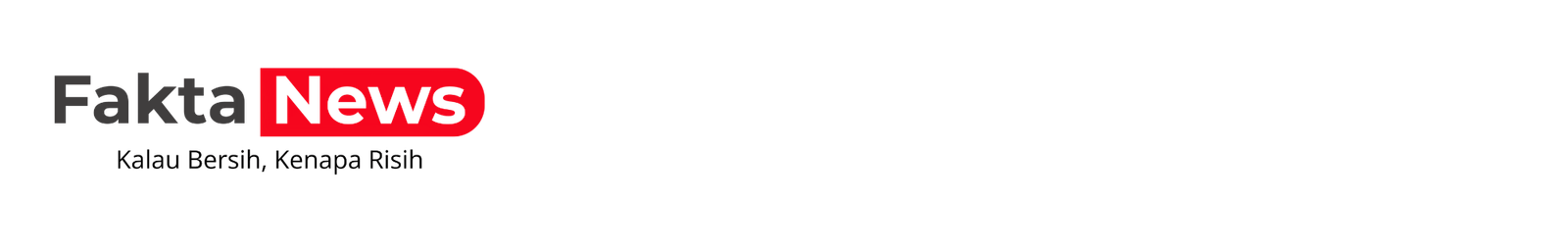Krisis Multidimensi yang Membatalkan Mimpi Kemakmuran
Oleh: Jhojo Rumampuk
Fakta News – Opini. Pohuwato hari ini sedang berdiri di titik nadir sejarahnya. Sebuah kabupaten yang dulu digadang sebagai “permata barat Gorontalo” kini menghadapi kenyataan pahit: kemakmuran yang dijanjikan dari tambang emas hanya tinggal retorika, berubah menjadi sumber penderitaan rakyatnya sendiri.
Yang terjadi di Pohuwato bukan sekadar krisis ekonomi atau politik, melainkan krisis multidimensi, sebuah katastrofi sosial, ekologis, dan moral pemerintahan yang perlahan menghancurkan sendi kehidupan daerah.
Kata katastrofi bukanlah hiperbola. Ia adalah kenyataan getir tentang bencana besar yang lahir bukan dari alam, tetapi dari tangan-tangan manusia yang lupa diri dalam mengejar emas.
Pada awalnya, tambang di Pohuwato disebut sebagai berkah. Narasi yang dibangun oleh para pejabat dan investor terdengar indah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, mengangkat ekonomi masyarakat.
Namun kenyataannya, di balik retorika itu, ribuan rakyat kecil kini terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan baru, kemiskinan yang ironisnya justru lahir dari kekayaan alam mereka sendiri.
Gunung dan sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini akan rusak, air keruh tercemar bahan kimia, sawah dan kebun kehilangan kesuburan, ikan di sungai mati, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya.
Tambang emas yang dijanjikan sebagai “Pintu Kemakmuran” kini justru menjadi luka kolektif bagi rakyat Pohuwato.
Sementara itu, keuntungan besar mengalir ke luar daerah, masuk ke saku para pemilik modal dan elite politik yang berdiri di balik perizinan. Rakyat Pohuwato hanya menjadi penonton di tanah sendiri dengan menyaksikan bagaimana emas mereka dijarah, lingkungan mereka dirusak, dan masa depan mereka dikorbankan.
Dampak sosial dari kekacauan tambang kini semakin terlihat. Konflik horizontal antar penambang, antara penambang lokal dan perusahaan, hingga antara rakyat dan aparat, menjadi pemandangan sehari-hari.
Ketika tambang menjadi rebutan, rasa persaudaraan di kampung-kampung hilang digantikan oleh kecurigaan, iri hati, dan ketakutan.
Tak jarang, suara protes rakyat dibalas dengan intimidasi. Beberapa aktivis lingkungan di Pohuwato mengaku menerima ancaman, sebagian bahkan dikriminalisasi hanya karena bersuara menolak ketidakadilan.
Kebebasan sipil yang seharusnya dijamin oleh konstitusi, kini seolah lenyap di balik bayang-bayang kepentingan tambang.
Lebih jauh, krisis sosial ini juga telah merusak nilai-nilai moral masyarakat. Anak muda tumbuh di tengah narasi bahwa kekayaan cepat bisa datang dari tambang, tanpa kerja keras, tanpa pendidikan, tanpa arah hidup yang pasti.
Krisis multidimensi Pohuwato juga merupakan krisis politik yang dalam. Tambang telah menciptakan oligarki lokal, jaringan kekuasaan antara politisi, pengusaha, dan aparat yang saling menopang demi kepentingan ekonomi.
Mereka mengatur izin, mengendalikan narasi publik, bahkan mempengaruhi arah kebijakan daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi maupun Kabupaten yang seharusnya menjadi alat kontrol rakyat, sering kali tak lebih dari perpanjangan tangan kepentingan bisnis tambang.
Kritik publik dibungkam, pengawasan lingkungan melemah, dan kebijakan daerah disesuaikan dengan selera para pemodal.
Inilah bentuk kolonialisme modern di tanah sendiri, ketika rakyat tak lagi berdaulat atas bumi dan airnya.
Di tengah situasi seperti ini, pemerintah daerah sering berkilah bahwa tambang adalah “jalan satu-satunya” menuju pembangunan.
Namun argumen itu rapuh. Karena bagaimana mungkin kita berbicara tentang pembangunan jika rakyatnya kehilangan kesehatan, tanahnya kehilangan kesuburan, dan lautnya kehilangan ikan?
Pembangunan yang menghancurkan manusia bukan pembangunan, melainkan perampasan masa depan.
Kerusakan lingkungan di Pohuwato kini mencapai titik kritis. Hutan-hutan gundul, air sungai beracun, dan sedimentasi besar-besaran menghancurkan ekosistem pantai dan pesisir.
Ironinya, semua ini terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa aktivitas tambang “sudah sesuai prosedur.”
Padahal, data dan fakta lapangan menunjukkan hal sebaliknya, penambangan liar dibiarkan, limbah tambang mencemari sungai, dan pengawasan lingkungan praktis lumpuh.
Ketika alam sudah rusak, bencana akan datang dalam bentuk lain seperti, banjir, tanah longsor, dan krisis air bersih.
Pohuwato seakan berjalan menuju kehancuran ekologis yang tak bisa dibalikkan.
Namun krisis yang paling berbahaya justru bukan pada tambangnya, melainkan pada jiwa para pemimpinnya. Krisis moral inilah yang membuat kebijakan kehilangan nurani.
Ketika pejabat publik lebih sibuk menghitung cuan daripada melindungi rakyat, maka sesungguhnya bencana itu sudah datang dan hanya saja belum disadari.
Pemimpin sejati seharusnya berdiri di depan rakyat, bukan di belakang investor. Pemimpin sejati seharusnya berbicara untuk yang tak bersuara, bukan menutup telinga dari jeritan warga yang kehilangan tanah dan rumahnya.
Tapi sayangnya, Pohuwato kini kekurangan sosok seperti itu. Yang ada justru parade pejabat yang berlomba-lomba menjaga citra, sementara rakyat menanggung beban dari setiap kebijakan yang gagal.
Pohuwato tidak butuh lagi janji-janji baru. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kolektif, keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang gagal, bahwa tambang bukan solusi tunggal, bahwa kemakmuran sejati tidak datang dari perut bumi, melainkan dari keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Rakyat Pohuwato harus kembali berdaulat atas tanah dan nasibnya sendiri. Pemerintah harus berhenti menjadi pelayan modal, dan mulai menjadi pelindung rakyat.
Sudah saatnya kita menagih tanggung jawab moral dari setiap pejabat, dari setiap perusahaan, dan dari setiap lembaga negara yang selama ini diam melihat penderitaan rakyat tambang.
Bahwa Pohuwato pernah punya emas, tapi kehilangan kemanusiaan.
Bahwa Pohuwato pernah punya sumber daya alam, tapi tak pernah punya keadilan. Dan bahwa mimpi kemakmuran yang dulu dijanjikan, akhirnya batal karena rakusnya manusia dan matinya keberpihakan.
Krisis multidimensi Pohuwato bukan sekadar masalah tambang, ini adalah cermin dari kegagalan tata kelola, kegagalan moral, dan kegagalan politik.
Kita boleh membangun gedung tinggi, menggali emas sebanyak mungkin, dan menandatangani kontrak investasi terbesar, tetapi selama rakyat menderita dan lingkungan mati, semua itu tak lebih dari kemakmuran semu.
![]()