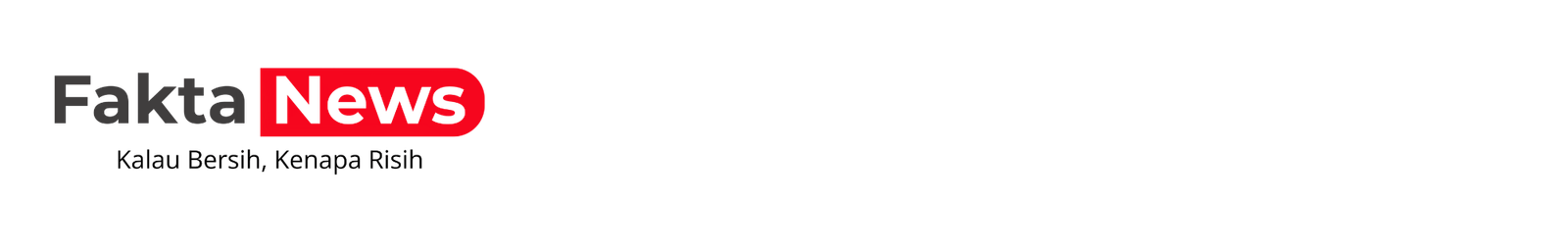Oleh : Jhojo Rumampuk | Ketua DPD PJS Gorontalo
Tulisan ini berusaha mengkaji fenomena maraknya konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam di daerah yang tidak hanya sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif, tetapi juga karena adanya kesepakatan-kesepakatan politik di balik layar yang berpotensi menjadi bentuk kejahatan jabatan.
Dalam konteks tersebut, masyarakat kerap menjadi korban dari politik kepentingan yang mengorbankan ruang hidup secara sistemik dan terstruktur.
Dalam sistem demokrasi, seharusnya kebijakan publik lahir dari kebutuhan rakyat dan dibentuk dengan prinsip keterbukaan, partisipasi, serta keadilan.
Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan sektor sumber daya alam, agraria, dan lingkungan justru menjadi instrumen kekuasaan untuk menjamin keberlangsungan relasi ekonomi-politik antara elite pemerintahan dan korporasi.
Kesepakatan politik yang terjadi antara pejabat publik dan pelaku usaha kerap melahirkan bentuk baru kejahatan jabatan, yakni pengambilan keputusan atau penerbitan izin atas nama kepentingan publik, namun sesungguhnya didasari oleh relasi transaksional dan politis.
Kejahatan jabatan tidak selalu harus dilihat dalam konteks suap atau gratifikasi. Tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan, misalnya dalam penetapan izin usaha tambang, alih fungsi kawasan hutan, atau pemanfaatan lahan masyarakat adat dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan hukum yang berdampak pada hilangnya hak-hak dasar masyarakat.
Penyelenggara negara dalam hal ini menjadi bagian dari struktur yang memfasilitasi perampasan ruang hidup masyarakat.Proses perumusan kebijakan dan perizinan seringkali tidak melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat terdampak.
Dialog sosial, analisis AMDAL, hingga konsultasi publik hanya menjadi formalitas belaka. Pada akhirnya, masyarakat berada dalam posisi inferior, tidak mampu menolak karena keputusan telah dibuat di ruang elit yang tertutup.
Ini bertentangan dengan prinsip free, prior, and informed consent dalam perlindungan hak masyarakat adat dan lokal.Ketika ruang hidup masyarakat, hutan, tanah, air, dan udara telah dikuasai atau dikontrol oleh korporasi melalui legalitas yang cacat prosedur, maka yang terjadi adalah perampasan ruang hidup secara legal formal.
Ini tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memiskinkan masyarakat dan merusak tatanan sosial yang telah ada.
Di berbagai daerah, termasuk di Gorontalo, fenomena kian terang: masyarakat bukan lagi sebagai subjek utama dalam pembangunan, melainkan objek dari kesepakatan-kesepakatan elitis yang ditentukan oleh aktor politik dan pemegang kekuasaan.
Ironisnya, kesepakatan itu sering dikemas dalam bahasa “pembangunan”, “investasi”, atau “kemajuan daerah”, padahal yang terjadi adalah bentuk lain dari perampasan ruang hidup masyarakat yang berlangsung secara sistematis.
Dalam lingkaran itulah, kejahatan jabatan tumbuh subur. Perizinan dipermudah bagi korporasi besar, tanah rakyat dengan mudahnya berubah status menjadi aset negara atau wilayah konsesi tambang, dan aturan yang seharusnya melindungi warga justru menjadi senjata legal untuk menyingkirkan mereka dari tanah kelahiran sendiri.
Semua terjadi dalam sunyi, di balik meja rapat, surat rekomendasi, dan tanda tangan pejabat. Kita menyaksikan bagaimana masyarakat kecil ditekan secara halus namun pasti. Mulai dari pembatasan akses terhadap lahan, air bersih, hingga pencemaran udara yang dibiarkan karena ‘demi investasi’.
Di titik ini, pertanyaan yang wajib kita ajukan: siapa sesungguhnya yang dilayani negara itu rakyat atau pemilik modal?
Banyak warga yang awalnya diajak “berdialog”, tetapi nyatanya diarahkan untuk menerima realitas yang telah diputuskan di atas. Ruang partisipasi semu dibentuk, hanya sebagai formalitas untuk memenuhi prosedur hukum, bukan untuk mendengar aspirasi sesungguhnya.
Yang lebih tragis, ketika masyarakat mulai bersuara, muncul instrumen tekanan intimidasi, pelabelan “provokator”, bahkan kriminalisasi. Semua itu seolah menjadi SOP tak tertulis dalam mengamankan kesepakatan politik yang telah dibuat oleh penguasa dan pengusaha.
Ketika kita membiarkan semua terjadi, maka kita akan menjadi tamu di tanah sendiri, hidup di bawah bayang-bayang pabrik dan tambang, bukan di tengah alam yang menopang kehidupan.
Siapa yang sesungguhnya diuntungkan?
Siapa yang dikorbankan?
Dan sampai kapan kita harus membayar harga dari kesepakatan politik yang tak pernah kita setujui?
Sebagai sebuah provinsi kecil di utara Pulau Sulawesi, menyimpan potensi luar biasa dalam sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Namun di balik narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, media turut merekam sisi lain Gorontalo.
Yaitu konflik agraria, eksploitasi tambang ilegal, lemahnya penegakan hukum, serta relasi kuasa yang timpang antara pengusaha, pejabat, dan rakyat kecil.
Dalam kacamata media, Gorontalo bukan hanya soal potensi, tapi juga potret ketidakadilan. Ketika suara masyarakat terpinggirkan, media menjadi ruang perlawanan terakhir untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi dan menantang narasi dominan yang dibentuk oleh elite kuasa.
Maka, jurnalisme di Gorontalo tidak hanya memotret peristiwa, tetapi juga menjadi saksi sejarah atas perjuangan rakyat melawan ketimpangan dan kezaliman yang terstruktur. (Bersambung)
![]()