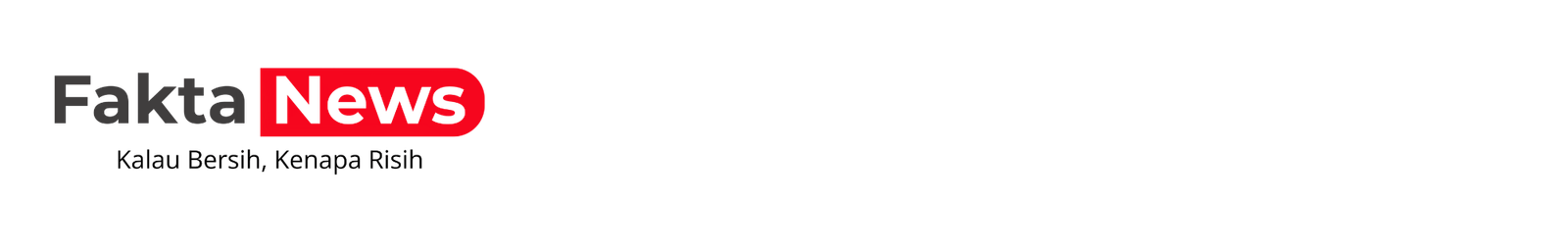Fakta News – Tajuk. Pernyataan dr. Alaludin Lapananda, orang tua dari Anggota DPRD Kota Gorontalo, Alwi Kusuma Lapananda kepada beberapa Aktivis Gorontalo yang menyebut bahwa polemik video mesra anaknya dengan Anggota DPRD Gorontalo Utara Dheninda Chaerunisa hanyalah ulah “Kader Nasdem” yang tidak ingin Dheninda sebagai Ketua Komisi III DPRD Gorut, telah menimbulkan gelombang diskusi baru di ruang publik Gorontalo.
Namun, di balik narasi pembelaan tersebut, muncul pertanyaan mendasar, apakah ini bentuk klarifikasi yang logis, atau sekadar upaya mengalihkan isu dari persoalan moral dan etika pejabat publik?
Pertama-tama, perlu ditegaskan bahwa inti polemik bukanlah soal intrik politik internal partai, melainkan rekaman visual yang menunjukkan perilaku tidak pantas dua pejabat publik di ruang publik.
Video yang memperlihatkan dua anggota legislatif berbeda daerah yang bukan pasangan sah tengah berpelukan dan berciuman, jelas mengundang reaksi keras masyarakat.
Dalam konteks etika jabatan, publik tidak sedang menilai soal cinta pribadi, melainkan tanggung jawab moral seorang pejabat di ruang digital yang terbuka.
Menyebut bahwa polemik ini hanya rekayasa politik kader tertentu, adalah bentuk pengalihan isu (issue diversion) yang klasik.
Pembelaan semacam ini bukan hanya melemahkan nilai objektivitas publik, tapi juga mengecilkan makna integritas jabatan legislatif.
Jika setiap persoalan etika dikemas sebagai “serangan politik”, maka tak akan ada lagi ruang bagi penegakan moral di lembaga rakyat.
Politik Sebagai Kambing Hitam ?
Membawa-bawa nama partai atau kader Nasdem dalam polemik ini tanpa bukti yang jelas hanya memperkeruh keadaan.
Kritik publik terhadap video mesra itu lahir secara spontan dari reaksi sosial dan kultural masyarakat Gorontalo yang menjunjung tinggi nilai adat, agama, dan kesopanan sosial.
Menuduh adanya “tangan politik” di balik viralnya video seolah mengabaikan fakta bahwa media sosial bekerja dalam logika keterbukaan, bukan perintah partai.
Lebih jauh, tuduhan tersebut bisa dianggap sebagai upaya “Framing Defensif” untuk melindungi citra anak sendiri tanpa memperhitungkan dampak moral terhadap publik dan lembaga DPRD.
Padahal, jika seorang pejabat publik berani tampil di ruang digital dengan perilaku yang menjurus pada pornoaksi, maka tanggung jawab etiknya tidak bisa ditutup dengan alasan politik.
Sebagai pejabat publik, baik Alwi Lapananda maupun Dheninda Chaerunisa memiliki beban moral lebih tinggi dibanding warga biasa.
Etika publik menuntut sikap berhati-hati dalam setiap perilaku, termasuk dalam urusan pribadi yang berpotensi disaksikan publik.
Dalam pandangan Ilmu Etika Politik dan Administrasi Publik, perilaku pejabat yang melanggar nilai moral masyarakat dapat dikategorikan sebagai “misconduct of public image” kesalahan yang mencederai wibawa jabatan.
Dalam konteks budaya Gorontalo, yang masih memegang kuat nilai “Adati hula-hula to syara’a, syara’a hula-hula to Kuru’ani” (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Qur’an), adegan seperti itu tidak bisa dianggap sepele.
Karena bukan hanya mencoreng nama pribadi, tapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif itu sendiri.
Ironisnya, pembelaan yang berlebihan dari pihak keluarga justru berpotensi memperdalam luka kepercayaan publik.
Alih-alih menenangkan situasi, narasi “ini ulah kader Nasdem” malah memunculkan kesan bahwa sang orang tua tidak memahami esensi kritik masyarakat.
Pembelaan emosional terhadap anak boleh saja, tetapi ketika dilakukan di ruang publik dengan menyerang pihak lain tanpa dasar, itu sudah masuk wilayah penciptaan opini yang bias.
Lebih buruk lagi, sikap ini berpotensi memicu konflik horizontal di internal partai karena menyeret nama kader tanpa klarifikasi resmi.
Padahal, dalam tradisi politik yang sehat, setiap tuduhan harus disertai bukti, bukan perasaan atau spekulasi pribadi.
Publik Butuh Keteladanan, Bukan Alasan
Poin terpenting dari seluruh polemik ini adalah publik tidak mencari kambing hitam, tetapi tanggung jawab.
Jika benar video itu direkam lama dan bersifat pribadi, maka tidak seharusnya rekaman video tersebut diedarkan atau didistribusikan lewat konten media sosial Instagram.
Namun ketika pembelaan berubah menjadi serangan balik terhadap pihak lain, masyarakat akan menilai bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi.
Sebagai orang tua, wajar membela anak. Tapi sebagai tokoh masyarakat dan mantan pejabat (jika memang demikian), dr. Alaludin Lapananda seharusnya mendorong introspeksi, bukan memicu perpecahan narasi.
Sebab dalam logika publik, pembelaan tanpa tanggung jawab justru memperkuat dugaan bahwa ada kesalahan yang nyata.
Polemik video dua pejabat legislatif ini seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan ajang saling tuding.
Karena yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi dua orang, tetapi martabat lembaga DPRD dan nilai moral Gorontalo sebagai daerah yang menjunjung adat dan agama.
Kita tidak sedang berbicara soal siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang mampu menjaga kehormatan jabatan publik.
Dan dalam konteks itu, publik tidak butuh pembelaan emosional dari orang tua pejabat, melainkan kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan moral.
Redaksi Fakta News
![]()